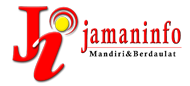Sebentar lagi tahun 2017 akan berakhir. Sepanjang tahun 2017 berbagai dinamika politik di tanah air telah menjadi perhatian publik dan media. Banyak analis menganggap dinamika tersebut sebagai proxy menuju pertarungan politik 2019—terutama pemilihan presiden. Dinamika politik ini juga menunjukkan bahwa ruang politik formal tidak hanya menjadi pertarungan elit politik, tapi juga menguatnya politik sektarian dalam kompetisi politik elektoral.
Yang juga penting menjadi catatan atas dinamika politik sepanjang tahun 2017 adalah upaya politisasi isu korupsi. Banyaknya politisi parpol yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kekuatiran parpol yang terlibat akan terkena dampak elektoral, membuat “perseteruan” KPK dan DPR cukup mewarnai pemberitaan sepanjang tahun 2017. Namun semua ”kegaduhan” politik sepanjang tahun 2017 ini tidak mempunyai dampak signifikan terhadap kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis 12 September 2017, menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemerintahan Jokowi-JK terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Didapatkan tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK tahun 2015 sebesar 50,6 persen. Kemudian, pada 2016 naik menjadi 66,5 persen. Sementara pada tahun ini naik menjadi 68,3 persen.
Fenomena Politik Sektarian
Politik sektarian dengan menggunakan isu agama, ras, suku adalah penumpang gelap dari reformasi yang memajukan nilai demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial. Politik sektarian yang tadinya diangap sebagai pinggiran, tiba-tiba saja menjadi perhatian publik ketika digunakan sebagai instrumen politik dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Politik sektarian yang awalnya sebagai fenomena persekusi kelompok intoleran bertransformasi menjadi kekuatan politik nyata yang membelah masyarakat.
Dampak dari Pilgub DKI Jakarta adalah kembali digunakanya politik sektarian atau politik identitas berbasis agama sebagai referensi publik dalam politik elektoral. Temuan survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) di delapan provinsi menunjukan bahwa politik identitas sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Sebelum Pilgub DKI Jakarta angkanya dibawah 50 persen, tapi setelah Pilgub angkanya diatas 50 persen.
Sementara menurut Edward Aspinnal dan Eve Warburton dalam tulisannya “Indonesian democracy: from stagnation to regression? di portal The Strategist, 17 Agustus 2017, mengatakan bahwa politik sektarian juga berkembang dalam wacana kesenjangan sosial di Indonesia dengan menggunakan wacana etno-religius. Wacana ini muncul dari elit politik dalam memandang distribusi kekayaan yang tidak adil. Wacana yang dimunculkan adalah pihak yang kaya dimiliki oleh etnis China dan Kristen, sementara kaum miskin mayoritas adalah msyarakat muslim.
Presiden Jokowi sendiri dalam merespon fenomena ini mengakui masih ada gesekan yang terjadi saat pemilihan kepala daerah yang menggunakan isu suku dan agama. Presiden Jokowi menegaskan bahwa politik dan agama harus dipisah, tidak boleh disatukan. Jangan sampai dicampuradukkan antara politik dan agama, dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik.
Namun ini bukan berarti bahwa Presiden Jokowi menihilkan inspirasi dan perspektif agama dalam berpolitik. Sedari awal, presiden telah menunjukkan kedekatan dan kemitraan kepada kelompok-kelompok pendidikan maupun syiar keagamaan ke dalam pembangunan dan perwujudan cita-cita kebangsaan. Dari mulai menetapkan Hari Santri Nasional, penataan penyelenggaraan haji sampai pengembangan dan penguatan ekonomi pesantren.
Politisasi Korupsi
Tahun 2017 juga menjadi tahun dimana politisasi korupsi terjadi dalam panggung politik nasional. Politisasi ini sangat kental karena banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif dari berbagai parpol yang ditangkap. Menurut data KPK, 32 persen dari tahanan KPK adalah politisi. Sampai Juni 2017, sebanyak 78 tahanan KPK merupakan kepala daerah, dan 134 orang lainnya merupakan anggota legislatif, baik pusat maupun daerah.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), selama dua tahun belakangan ini sebanyak 11 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Sebagian besar para kepala daerah merupakan kader parpol. Seperti diketahui korupsi kelas kakap umumnya melibatkan pejabat yang juga kader parpol, seperti kepala daerah, anggota DPR RI, anggota DPRD atau menteri.
Praktek korupsi yang melibatkan politisi di eksekutif dan legislatif adalah dampak dari industrialisasi politik yang terjadi pasca reformasi. Politik elektoral menjadi sangat mahal, karena itu memerlukan modal besar untuk mendapatkan dukungan dan memenangkanya. Akibatnya, pejabat publik di eksekutif dan legislatif, baik pusat dan daerah, harus mengembalikan modal politik tersebut. Praktek korupsi adalah jalan pintas untuk mendapatkanya.
Sepanjang tahun 2017 politisasi kasus korupsi terjadi dalam dua feneomena yang menarik perhatian publik.
Pertama, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Besar dugaan publik, pansus ini untuk memperlemah KPK serta langkah awal merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebaliknya, kalangan politisi DPR menganggap tujuan dibentuknya Pansus justru untuk memperkuat dan membenahi tata kelola KPK.
Presiden Jokowi dalam Sidang Bersama DPD-DPR menyatakan bahwa pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK. Presiden juga mengajak seluruh rakyat Indonesia menjadikan korupsi sebagai musuh bersama dan memeranginya. Survei CSIS memperlihatkan bahwa mayoritas responden sebanyak 76,9 persen meyakini Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen memperkuat KPK.
Kedua, politisasi korupsi dalam kasus korupsi e-KTP yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Setyo Novanto. Nilai proyek pengadaan e-KTP lebih dari Rp 6 triliun. Namun, hanya 51 persen anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut. Kasus ini menjadi kental nuansa politik karena ditengarai melibatkan sejumlah politikus lintas parpol anggota Komisi II DPR periode 2009–2014.
Tantangan Politik 2018
Tahun 2018, Indonesia akan melakukan hajatan politik besar pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Keberhasilan politik sektarian dalam Pilgub DKI Jakarta besar kemungkinan akan direplikasi dalam Pilkada di wilayah lain. Pilkada serentak Juni 2018 nanti juga akan terkait dengan Pileg dan Pilpres 2019.
Parpol yang mengusung bakal calon kepala daaerah akan memandang kemenangan Pilkada ini sebagai fondasi untuk sukses dalam Pileg dan Pilpres 2019. Semakin banyak menguasai kepala daerah dianggap langkah strategis parpol guna mobilisasi suara dalam pemilu, karena dengan jabatan kepala daerah kapasitas untuk mobilisasi dukungan elektoral lebih maksimal.
Menurut BBC Indonesia, wajah perpolitikan Indonesia dalam dua tahun ke depan akan diwarnai persaingan tajam dua kekuatan politik dominan yang mengakibatkan perpecahan politik di tingkat masyarakat sulit disembuhkan. Sementara menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), pembelahan yang terjadi pasca Pilpres 2014 muncul kembali dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena itu LSI meramalkan polarisasi seperti itu akan kembali terulang dalam Pilpres 2019 (BBC Indonesia, 19 April 2017).
Disinilah pentingnya perhatian dan kegigihan semua komponen bangsa senantiasa menjaga persatuan nasional. Jangan sampai untuk kepentingan politik kekuasaan mengorbankan yang prinsip, yaitu persatuan. Dibutuhkan komitmen para politisi kepada Pancasila, kebhinekaan dan persatuan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan. Jangan berikan ruang kepada kelompok-kelompok sektarian dalam kampanye politik baik terbuka maupun tertutup. Kita wujudkan politik sebagai ruang untuk meningkatkan keadaban publik dan pengabdian untuk bangsa dan tanah air.
Eko Sulistyo
Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Kantor Staf Presiden.