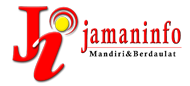Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam program Nawa Cita telah berkomitmen untuk menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Pasalnya, pelanggaran tersebut hingga saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia.
Komitmen tersebut kembali diperbarui oleh Pemerintah dengan mengundang para korban dan keluarga korban Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok dan Tragedi 1965 ke Istana Negara pada 31 Mei 2018 lalu.
Namun, seolah mereduksi komitmen tersebut, Jaksa Agung H.M Prasetyo menyampaikan bahwa penyelesaian pelanggaran tersebut susah dilakukan lantaran kesulitan untuk mencari bukti, saksi, pelaku dan korban. Menurutnya, hasil penyelidikan Komnas HAM hanya berupa asumsi dan opini.
Berkaitan dengan hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari IKOHI, Indonesia Legal Roundtable (ILR), KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan (LKK), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai bahwa pernyataan Jaksa Agung tersebut memiliki kesalahan mendasar berdasarkan sistem hukum dan peradilan baik pidana maupun pelanggaran HAM berat. Mereka juga meminta kepada Presiden untuk mencopot Jaksa Agung H.M Prasetyo.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima JamanInfo.com menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU 26/2000, Pasal 20 ayat (1) UU 26/2000, Pasal 21 ayat (1) UU 26/2000, Pasal 10 UU 26/2000 dan Pasal 2 ayat (1) KUHAP memiliki arti bahwa Komnas HAM bertanggung jawab hingga mencari, menemukan ada tidaknya peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM melalui bukti permulaan yang cukup (menurut putusan MK adalah 2 alat bukti).
“Menemukan tersangka adalah bagian dari penyidikan. Penyidik adalah Jaksa Agung sehingga yang memiliki kewajiban menemukan pelakunya adalah Jaksa Agung,” tegas mereka.
Oleh karena itu, lanjut rilis tersebut, bolak balik berkas antara penyidik (Jaksa Agung) dengan penyelidik (Komnas HAM) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20 UU 26/2000 hanyalah sebatas bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan menurut Undang-undang bukan adanya bukti mengenai pelakunya.
“Ketentuan ini juga sesuai dengan pasal 2 ayat (1) KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” ungkapnya.
Menurut mereka, apabila Jaksa Agung terlalu sibuk untuk menjalankan kewajiban hukumnya sesungguhnya pasal 19 ayat 1g UU 26/2000 dan pasal 5 ayat 1b KUHAP mengatur penyelidiki dapat melakukan beberapa tindakan atas perintah penyidik.
Selain itu, jika Jaksa Agung merasa tidak mampu menjalankan kewajiban hukumnya Pasal 21 ayat (3) UU 26/200 juga memberikan kemungkinan mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
“Artinya Jaksa Agung dapat menganggap Komnas HAM sebagai penyidik ad-hoc bahkan masyarakat,” tandas keterangan itu.
Mereka menilai, prnyataan Jaksa Agung menunjukkan dua kemungkinan yaitu Jaksa Agung tidak mengerti hukum yang berlaku atau Jaksa Agung paham hukum tetapi sengaja mencari-cari alasan agar tidak menjalankan kewajiban hukumnya yang bersumber dari undang-undang dan arah kebijakan Presiden.
Baginya, satu dari dua alasan tersebut cukup untuk membuat siapapun orangnya dicopot, diganti dengan yang lebih memiliki kapasitas atau tanggung jawab, serta searah dengan kebijakan Presiden yaitu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana tertuang dalam Nawacita.
“Tidak digantinya Jaksa Agung atau pejabat negara lainnya yang semacam ini akan membuat pincang pemerintahan dan kebijakan Presiden,” pungkas rilis tersebut.
Reporter: Eko “Gajah”