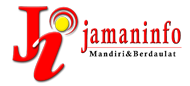“Politik barangkali menjadi satu-satunya profesi yang tidak membutuhkan persiapan pemikiran yang memadai”, kata Robert Loius Stevenson (1859-1894). Kutipan itu saya ambil tanpa tahu konteks kalimat dan tema tulisan secara lengkap. Tapi setidaknya frase “persiapan pemikiran yang memadai” itu bisa kita tafsirkan dari beberapa pengertian.
Persiapan pemikiran yang kurang memadai bisa jadi mengacu pada ketidakmampuan berpikir secara matang dalam pengertian ideologis—bukan hanya taktik. Sedangkan dari segi taktik politik yang terjadi di masyarakat kita, kita tentu tahu bahwa satu-satunya jalan yang paling dijadikan taktik untuk mendapatkan kemenangan politik adalah dengan menggunakan “duit”.
Bahkan, politisi sendiri hanya yakin bahwa kalau mereka tidak punya uang, maka mereka pasti akan kalah dalam bertarung. Bahkan lebih baik tidak berpolitik dengan alasan karena tidak punya modal duit untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Politik menjadi tidak ideologi, tidak idealis. Politik kemudian berisi dengan prinsip “mengeluarkan modal untuk dapat posisi yang bisa membuat modal yang dikeluarkan bisa balik”.
Lalu, ketika kedudukan politik dianggap melahirkan status dan kekuasaan yang bisa mendatangkan otoritas akibat kedudukan yang diperoleh, mendapatkan posisi politik kemudian menjadi semacam capaian yang bisa membuat seseorang punya eksistensi diri yang mengembirakan dan bermakna (sesuai pemaknaan masing-masing). Bahkan kedudukan ini sebagai sebuah eksistensi dan melahirkan status sosial juga akan dikejar dengan mati-matian meskipun dengan kemampuan tidak memadai.
Inilah yang membuat orang kaya dengan uang berlebih akan memaksa anaknya untuk menjadi calon dan berkompetisi merebut kedudukan—meskipun sumber daya manusia dan kemampuan berpikir, bahkan kecakapan teknis seperti kemampuan berbicara, amat kurang memadai. Inilah yang memaksa orang kaya dan punya duit berlebih kemudian maju sebagai politisi dadakan dan bertarung dalam politik elektoral, tetapi tak punya modal personalitas dan modal sosial-budya yang memadai.
Tujuannya hanya ingin mendapatkan kedudukan, dapat gaji dan tunjanga bulanan dari kedudukan yang didapat, sembari merasa bisa mendapatkan relasi dari posisinya untuk membuat usahanya lebih lancar lagi. Kedudukan politik ingin didapat, kadangkala, selain untuk pemenuhan eksistensi diri dengan beroleh jabatan dan kedudukan, juga karena ingin mendapat posisi yang bisa mendukung usaha pribadinya lebih lancar karena posisi yang didapat bisa membangun relasi-relasi bisnis secara lebih luas.
Ada fenomena lain. Yaitu ada orang yang kadang begtu obsesifnya ingin mendapatkan kedudukan dan jabatan politik pada saat ia tak menyadari bahwa kemampuan dan kecakapan personal tidak memadai, jaringan massa tidak ada, serta modal logistik (duit) juga amat kurang. Di tengah budaya “money politic” yang masih mengakar, untuk memenuhi dukungan logistik bahkan akhirnya orang ini harus berhutang uang untuk menambah biaya politik yang amat tinggi.
Di antara calon yang berkompetisi berebut jabatan politik ini ada yang jadi (terpilih). Ada pula yang tidak. Bagi yang jadi dan mendapatkan posisi yang membuatnya punya gaji dan tunjangan bulanan, ada yang sudah bisa melunasi utangnya sebelum jabatan lima tahunnya habis. Tapi, celakanya, juga bahkan ada yang hingga jabatan lima tahunnya mau selesai, utangnya belum bisa dilunasi.
Dan bagi yang sudah terlanjur mengeluarkan uang banyak apalagi yang juha berhutang dan tidak jadi, maka sudah tentu ia seperti kalah berjudi. Dalam judi orang memasang uangnya untuk dipertaruhkan, kalau beruntung dan angkanya kena ia akan mendapatkan uang berlipat dari uang yang telah dipasang. Tapi kalau ia tak beruntung, uang yang telah keluar akan hilang dan tak bisa ditarik kembali. Saat seseorang maju di kompetisi pencalonan untuk anggota legeslatif, ratusan juta sudah dikeluarkan dengan tujuan menang. Tapi nyatanya ia kalah. Ratusan juta uang hilang.
Bagaimana kalau uang itu adalah uang utangan? Bagaimana kalau uang itu adalah hasil menjual semua aset dan harta miliknya seperti tanah, rumah, toko, mobil, sepeda motor, dan lain-lain? Tentu karena perjudian politik orang bisa jatuh miskin dan sengsara. Bagaimana jika semua harta dan aset sudah terjual tapi bahkan masih punya banyak hutang yang harus dibayar? Bagaimana dengan anak-anaknya yang masih kecil dan butuh sekolah? Bisa jadi, kalah dalam perjudian politik bagi seorang kepala keluarga sama dengan mematikan masa depan anaknya.
Membayangkan orang yang kalah judi politik seperti itu kita bisa merasakan kengerian yang luar biasa. Saya membayangkan ada seorang kepala rumahtangga yang sudah memiliki tabungan dan aset yang telah ia kumpulkan hampir separuh dari hidupnya yang awalnya dimaksudkan untuk mempersiapkan biaya pertumbuhan dan pendidikan anak, lalu suatu waktu ia tergoda seorang teman yang aktif di partai dan ia tergoda untuk ikut maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legeslatif di kabupaten. Ternyata biaya politik yang dikeluarkan cukup tinggi, bahkan harta dan aset yang dimilikinya habis, dan malah kurang yang kemudian membuatnya berhutang, tapi ternyata ia tidak jadi.
Membayangkan hal seperti itu tentu kita bukan hanya kasihan pada caleg yang gagal dan kehilangan banyak materi. Tentu bayangkan kita juga sampai menimbulkan pertanyaan bagaimana perasaan istri dan anaknya? Lalu kita akan merasakan bagaimana tingkat tekanan batin ketika orang telah kehilangan segalanya, materi, dan masa depan, dan jebakan hutang. Dan kita tahu, akhirnya ada pula orang yang gila dan “stressed” karena gagal mendapatkan jabatan. Kondisi “stressed” memang terjadi ketika jalan hidup buntu akibat semuanya habis dan merasa tak ada jalan.
Itu adalah fenomena yang harus dipecahkan bersama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena ini melibatkan relasi antar berbagai pihak, khususnya antara (calon) yang maju dan (calon) pemilih. Itu adalah benang kusut yang harus diurai. Bagaimana cara mengurainya. Ya tentunya dilihat satu persatu. Bisa melibatkan analiasa sosio-ekonomi, politik, budaya, dan mungkin juga butuh keterlibatan agama. Dari sisi agama, misalnya, apakah sudah ada fatwa, misalnya, bahwa MONEY POLITIC itu haram? Dari sisi sosio-ekonomi misalnya, apakah sudah ada riset bahwa yang cenderung hanya mau milih kalau ada amplop adalah kelas ekonomi tertentu, misal kelas bawah.
Lalu, selaku pribadi-pribadi, apakah kita cukup hirau tentang hal ini? Lalu kita meyakinkan diri kita bahwa kita tak boleh larut pada keadaan, lalu ya ikut-ikutan sambil bilang “Ah, gimana lagi, memang sudah gitu… Ya kita ikut aja yang penting kita untung… diambil yang menguntungkan saja!” Ataukah ini memang masalah serius di mana tiap-tiap individu maupun kelompok bertekad berbagi tugas untuk mengatasi masalah.
Nurani Soyomukti
(Kaki Gunung Jabung Karangan, 20/03/2018)