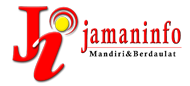Saudaraku, saya dilahirkan di sebuah dusun terkucil, ujung selatan Sukabumi-Jawa Barat, yang tak terlihat pada peta manual. Kepungan perbukitan dan terjal jalanan menyulitkan mobilitas; membuat kehidupan desa kami terpencil.
Dalam keterpencilan spasial, yang bisa membawa kesempitan mental, pemahaman atas kehidupan dan perkembangan dunia lain hanya bisa diterobos oleh ketersediaan bahan pustaka. Dunia kepustakaan inilah teropong kecil yang dapat membantu pengembaraan anak dusun menembus batas-batas ruang dan waktu.
Terima kasih tak terhingga pada kedua orang tua, guru kemanusiaan pertama dalam kehidupanku. Merekalah yang mengajariku baca-tulis; memperkenalkan dunia luas lewat kalam; menjadikan rumahnya sebagai “gudang buku” dan membacakan beragam literatur saat anak-anaknya mengelilingi meja makan.
Literasi memberi prakondisi mental untuk bersedia menerima hal-hal baru, menerobos dinding eksklusivisme primordial dengan membuka diri terhadap pengalaman yang lain, mentrasformasikan keyakinan lama dengan menerima pemahaman baru.
Demikianlah, buku membawa pengembaraan seorang anak udik-terpencil dengan mentalitas terkepung (under-siege mentality), yang memandang kelainan sebagai ancaman, menjadi seorang dengan mentalitas (relatif) terbuka, bisa melintasi sekat-sekat agama, etnis dan kelas sosial dan memandang keberlainan sebagai anugerah.
Keluasan horizon kehidupan yang diperkenalkan pustaka membuka kemungkinkan pergaulan lintas kultural. Dari pergaulan lintas kultural bisa dipetik pembelajaran, bahwa kebaikan itu bukan monopoli suatu golongan. Begitu pun keburukan, tidak bisa ditudingkan ke arah golongan yang lain. Setiap komunitas memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Tugas kepahlawanan adalah merajut kemanusiaan dan kebangsaan dengan mengawinkan elemen-elemen positif dari setiap komunitas lewat proses penyerbukan silang budaya.
Politik memainkan peran penting dalam mengambil sisi konstruktif dari proses penyerbukan silang budaya ini. Sungguh beruntung, desain politik Indonesia dalam memulai pendirian Negara ini telah mengambil pilihan yang tepat. Negara Indonesia adalah negara persatuan yang didirikan secara gotong royong dengan mengatasi paham perseorangan dan golongan. Dalam ungkapan Bung Karno, “Kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia—semua buat semua!”
Dalam usaha merawat negara persatuan, penyelenggara negara memainkan peran penting. Pentingnya peran penyelenggara negara ditekankan dalam pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”
Meski demikian, negara persatuan juga menuntut peran aktif warga negara, bukan hanya dalam menuntut haknya, tetapi terutama dalam menunaikan kewajibannya. Seperti diingatkan oleh Prof. Soepomo, “Dalam sistem kekeluargaan sikap warga negara bukan sikap yang selalu bertanya “apakah hak-hak saya?”, akan tetapi sikap yang menanyakan: apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia ini?…Inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua.” Pandangan Soepomo ini mendahului apa yang kemudian ditekankan oleh John F. Kennedy kepada rakyat Amerika Serikat pada 1961, “Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan oleh negara bagi dirimu; tanyalah apa yang dapat diberikan oleh dirimu kepada negara” (Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country).
Dari perjalananku menjejahi Indonesia dari ufuk ke ufuk, dari jarak dekat dengan bau keringat dan kaki-kaki kebangsaan, jelas terlihat bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, meski belum kunjung menemukan bentuk tata negara yang kongruen dengan watak bangsanya. Meski usaha pemerintahan dalam melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan menertibkan warganya masih relatif lemah, sambung rasa kebangsaan Indonesia masih relatif kuat. Masih kuatnya simpul kebangsaan inilah yang dapat menahan negara ini dari perpecahan.
Kuatnya ikatan rasa kebangsaan ini tidaklah sekadar mengandalkan pasak besar elit politik atau golongan mayoritas, melainkan oleh rajutan serat-serat tipis keindonesian, yang menampung inisiatif-inisiatif warga secara sukarela. Yakni gugusan inisiatif civic engagement dari keragaman agen sosial dalam usaha menyelesaikan problem-problem konkrit kewargaan dengan semangat keadaban publik yang non-diskriminatif.
Dari Danau Sentani di Papua hingga Danau Toba di Sumatra Utara, ada begitu banyak mata air kecemerlangan yang mengalir dari kearifan dan ketulusan pengabdian para tetua adat, guru-guru, pemuka agama, pengusaha, seniman, jurnalis dan tokoh-tokoh masyarakat sipil lainnya, yang dapat memberi pelajaran bahwa negara-bangsa ini memang banyak masalah, tetapi satu kepala manusia bisa menyelesaikan banyak hal. Apalagi, jika serat tipis agen-agen konstruktif ini bisa bertaut dalam semangat gotong-royong, membuka diri penuh cinta demi menjaga keseimbangan gerak sepasang sayap keindonesiaan: persatuan dan keadilan.
Seperti diingatkan oleh Bung Hatta (1928), “Bagi kami, Indonesia menyatakan suatu tujuan politik, karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan dan untuk mewujudkan tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.” Dalam kaitan ini, Bung Hatta kerap kali berseru: ”Hanya ada satu tanah air yang bernama Tanah Airku. Ia makmur karena usaha, dan usaha itu adalah usahaku.”
Yudi Latif
Kepala Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)