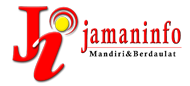Jaman, Opini (28/2) – Freeport McMoran telah memukul genderang untuk membawa pemerintah ke arbitrase. Pemerintah dituduh telah melanggar kontrak karya dengan mewajibkan Freeport untuk mengubah bentuk usaha pertambangan dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus. Menurut Freeport. ini niat sepihak pemerintah untuk mengakhiri KK.
Tuduhan Freeport bahwa pemerintah memaksa dirinya untuk mengubah bentuk usaha pertambangan KK menjadi IUPK adalah tidak benar. Pemerintah justru telah mencoba memahami kesulitan yang akan dihadapi oleh Freeport saat relaksasi yang diberikan kepada para pemegang KK berakhir pada 11 Januari 2017.
Tidak berdasar
Pangkal masalah yang memunculkan kegaduhan terletak pada Pasal 170 Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal 170 menentukan pemegang KK yang telah berproduksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya lima tahun sejak berlakunya UU Minerba tahun 2009. Ini berarti pada tahun 2014 semua pemegang KK sudah tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penjualan ke luar negeri. Namun, pada 2014 ternyata banyak pemegang KK tak mampu melakukan pemurnian di dalam negeri. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya yang memungkinkan pemegang KK melakukan ekspor dengan membayar bea keluar, tetapi tetap berkomitmen membangun smelter dalam jangka waktu tiga tahun.
Menjelang berakhirnya tiga tahun pada akhir 2016, ternyata sejumlah pemegang KK masih belum membangun smelter. Freeport salah satunya meski telah mengalokasikan dana untuk pembangunan smelter. Freeport tak kunjung membangun smelter karena ingin mendapat kepastian perpanjangan KK yang akan berakhir 2021. Dalam perhitungan Freeport, tanpa kepastian perpanjangan pembangunan smelter tak akan ekonomis.
Menghadapi kondisi belum terbangunnya smelter sementara terhadap Pasal 170 UU Minerba tak dilakukan perubahan, pemerintah pun harus mencari jalan keluar bagi pemegang KK yang belum mampu melakukan pemurnian di dalam negeri. Di sinilah kemudian diterbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017 dan sejumlah peraturan menteri (permen) ESDM. Dalam Pasal 17 Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan, pemegang KK dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama lima tahun dengan ketentuan mengubah bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK dan membayar bea keluar.
Apabila mencermati ketentuan tersebut, tak ada keharusan bagi pemegang KK untuk mengubah dirinya menjadi IUPK. Freeport, misalnya, bisa saja tetap mempertahankan KK. Hanya saja sesuai Pasal 170 UU Minerba, Freeport tidak dapat lagi melakukan penjualan ke luar negeri. Namun, jika Freeport ingin tetap melakukan penjualan ke luar negeri, Freeport harus mengubah diri dari KK ke IUPK. Pilihan ini ada di tangan Freeport dan pemerintah tidak sedikitpun melakukan pemaksaan.
Oleh karena itu, tuduhan Freeport bahwa pemerintah hendak mengakhiri KK sebelum 2021 adalah tidak benar. Justru pemerintah telah memberi jalan keluar bagi pemegang KK di tengah keinginan publik agar pemerintah tegas menjalankan Pasal 170 UU Minerba. Pemerintah menuai kritik. Bahkan, Permen ESDM No 5/2017 pun dibawa ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materi. Dalam konteks demikian, betapa tidak adilnya Freeport yang mengancam pemerintah ke arbitrase. Tak heran jika Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebut Freeport rewel. Pemegang KK lain seperti Vale tetap mempertahankan KK telah menunaikan kewajibannya dengan membangun smelter. Sementara PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu dimiliki oleh Newmont) telah mengubah bentuk menjadi IUPK agar tetap dapat melakukan penjualan ke luar negeri.
Arbitrase
Melihat kenyataan di atas menjadi pertanyaan apakah Freeport memiliki dasar yang kuat untuk menggugat pemerintah ke arbitrase? Atau ancaman membawa pemerintah ke arbitrase hanya gertakan belaka. Gertakan ini pernah dilakukan Freeport pada 2014 saat bea keluar ekspor diberlakukan. Ujungnya, Freeport membatalkan gugatannya. Ancaman Freeport terhadap Pemerintah Indonesia merupakan bentuk arogansi. Arogansi karena Freeport merasa sejajar dengan pemerintah. Penyebabnya, dengan KK pemerintah didudukkan sejajar dengan Freeport.
Secara hukum ini tidak masuk logika. Mana mungkin sebuah negara yang berdaulat dengan jumlah penduduk 250 juta diposisikan sejajar dengan pelaku usaha? Freeport sejak lama telah membangun persepsi yang salah dengan memosisikan Pemerintah Indonesia secara sejajar. Atas dasar itu, berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan pemerintah diminta untuk tidak diberlakukan atas dasar kesucian kontrak (sanctity of contract) atau ketentuan yang khusus akan mengenyampingkan ketentuan yang umum (lex specialis derogat legi generali).
Padahal, ketentuan khusus akan mengenyampingkan ketentuan umum jika produk hukumnya serupa. Jika perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, perjanjian yang akan gugur. Argumentasi Freeport bahwa pemerintah sejajar dengan dirinya karena Freeport mengabaikan dua dimensi dari pemerintah yang harus dibedakan.
Dimensi pertama, pemerintah sebagai subyek hukum perdata. Sebagai subyek hukum perdata pemerintah melakukan perjanjian dengan subyek hukum perdata lain. Semisal dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Dalam kapasitas sebagai subyek hukum perdata, kedudukan pemerintah memang sejajar dengan pelaku usaha. Namun, ada dimensi lain dari pemerintah, yaitu subyek hukum publik. Sebagai subyek hukum publik, posisi pemerintah berada di atas pelaku usaha dan rakyat. Fiksi hukum yang berlaku: ketika pemerintah membuat aturan, semua orang dianggap tahu tanpa perlu mendapat persetujuan. Pemerintah dapat memaksakan aturan yang dibuatnya dengan melakukan penegakan hukum.
Apabila rakyat atau pelaku usaha keberatan dengan aturan yang dibuat pemerintah sebagai subyek hukum publik, mereka dapat memanfaatkan proses uji materi, baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, bergantung pada produk hukumnya. Dua dimensi ini yang dinafikan Freeport. Tak heran jika Freeport hendak membelenggu kedaulatan hukum negara Indonesia dengan KK. Apabila demikian apa bedanya Freeport dengan VOC di zaman Belanda? Perlu dipahami pemerintah sebagai subyek hukum perdata tetap harus tunduk pada aturan yang dibuat pemerintah sebagai subyek hukum publik, semisal di bidang perpajakan.
Nasionalisme
Ancaman Freeport membawa pemerintah ke arbitrase justru telah membangkitkan rasa nasionalisme publik Indonesia. Publik marah. Saat ini pemerintah mendapat dukungan dari publik untuk bertindak tegas terhadap Freeport. Publik tak rela jika pemerintah mundur, bahkan berkompromi, karena ancaman Freeport. Freeport tak seharusnya memainkan tenaga kerjanya yang dirumahkan dengan alasan efisiensi untuk menekan pemerintah. Ini karena bola untuk tetap melakukan kegiatan operasi berada di tangan Freeport. Freeport bisa bertahan dengan KK asalkan melakukan pemurnian di dalam negeri atau tetap ekspor dengan mengubah status menjadi IUPK.
Freeport juga tidak seharusnya memainkan isu Papua, bahkan kehadiran pasukan marinir AS di Australia. Ada tiga alasan untuk ini. Pertama, dalam kisruh kali ini, pemerintah sudah bijak untuk memberi jalan keluar bagi Freeport yang ingin menang sendiri dan menuntut pemerintah tunduk pada KK dengan mengabaikan Pasal 170 UU Minerba. Sesuatu yang tak mungkin dilakukan pemerintah di era Indonesia yang demokratis. Kedua, saat ini pemerintahan di Indonesia dipimpin seorang yang berlatar belakang pengusaha seperti juga Presiden AS Donald Trump. Presiden Jokowi seperti Trump dalam membuat kebijakannya bisa sangat tegas dengan mengedepankan kepentingan nasional atau Indonesia first.
Ketiga, Freeport tidak bisa menggunakan tangan pemerintahnya untuk melakukan intervensi karena memang posisi Freeport tidak terlalu baik. Mana mungkin Pemerintah AS melakukan pembelaan terhadap pelaku usahanya dengan melakukan intervensi, bahkan menggunakan kekerasan padahal tindakan pelaku usaha itu salah. Pemerintah Indonesia tidak sedang menzalimi Freeport. Seharusnya Freeport paham negeri ini sudah mengalami pahitnya penjajahan di masa lalu dan pemerintah tidak dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan suara rakyat. Pendekatan dengan ancaman ataupun mendikte, bahkan merongrong kedaulatan, bukanlah pendekatan yang tepat jika Freeport ingin tetap berbisnis di Indonesia.(*)
Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional UI, Depok