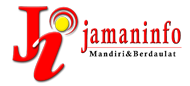Jaman, Opini (18/12) – Sekalipun pemerintah berusaha menutup-nutupinya, semakin jelas bahwa saat ini Indonesia di tepi jurang krisis energi. Dikhawatirkan pada saat yang hampir sama akan juga terjadi krisis beras. Seperti juga di sektor perberasan, Indonesia telah menjadi importir bersih minyak bumi.
Ketergantungan masyarakat pada beras dan BBM sudah pada taraf yang parah, yang diakibatkan oleh ketergantungan pada nasi, sepeda motor dan mobil pribadi. Gejala ini menunjukkan bahwa, kebijakan pangan didikte oleh kebijakan perberasan, kebijakan energi didikte oleh kebijakan transportasi, kebijakan transportasi didikte oleh kebijakan industri yang memihak industri otomotif asing.
Wacana krisis energi ataupun pangan berpotensi menyembunyikan asumsi bahwa kita seolah bisa tumbuh terus tanpa batas, terutama dari segi konsumsi energi atau pangan perkapita. Pemerintah, di manapun di dunia, selalu manargetkan pertumbuhan ekonomi, seolah-olah tumbuh itu hal yang selalu baik.
Model pembangunan kita saat ini jelas growth-obsessed. Obsesi pertumbuhan ini mensyaratkan disiplin perencanaan teknokratik terpusat ,yang seringkali meremehkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dan kreatif di tingkat grass-root pada kelompok nelayan, petani, dan perajin di berbagai ekonomi skala kecil di daerah-daerah yang tersebar luas di seluruh Nusantara.
Keterbatasan yang jelas adalah keterbatasan ruang. Bagaimana ruang diperebutkan secara zero-sum game telah ditunjukkan secara brutal di jalan-jalan kita. Ada paradoks yang penting kita cermati: penggunaan kendaraan bermotor semula dimaksudkan untuk “menghemat waktu”, namun ternyata kita justru “kehilangan waktu” di jalan. Semakin banyak mobil dan sepeda motor ternyata justru menyebabkan kekurangan waktu dan ruang.
Kita mesti mengingat peringatan Ivan Illich 40 tahun yang lalu, bahwa masyarakat dengan konsumsi energi tinggi adalah jalan bagi inefisiensi transportasi, polusi, dan ini yang terpenting adalah ketidakadilan dalam masyarakat. Sampai tingkat konsumsi energi perkapita tertentu, energi masih berdampak positif. Lebih tinggi dari itu, konsumsi energi justru mulai bersifat destruktif. Artinya, korelasi positif antara energi dan lingkungan hanya berlaku terbatas hingga satu ambang tertentu. Lebih dari ambang batas ini, energi mulai merusak lingkungan.
Lebih jauh, Illich menyebut bahwa masyarakat yang digolongkan berdasarkan kecepatan mobilitasnya menunjukkan tingkat konsumsi energi per kapita masyarakat yang sakit, seperti tubuh yang sakit akibat kelebihan kalori dalam gula darah. Penyakit masyarakat ini wujud dalam kesenjangan sosial ekonomi. Bahkan, konsumsi energi berlebihan akan justru menghasilkan kelumpuhan sosial-budaya.
Istilah krisis energi tidak cukup dilihat dari sisi pasokan saja, dan diartikan semata pada ketidakmampuan kita untuk menghasilkan sumber-sumber energi baru, terutama yang terbarukan, sementara konsumsi energi kita seolah boleh meningkat tanpa batas. Krisis energi juga harus diartikan ketidakmampuan mengendalikan keinginan kita untuk hidup berlebihan, bahkan dengan mengeksploitasi alam.
Penting untuk mencermati sinyalemen CEO Unilever yang mengatakan bahwa: jika umat manusia harus mengikuti gaya hidup Eropa, kita membutuhkan 3 bumi, dan jika meniru AS, kita membutuhkan 5 bumi. Pada titik ini, pemikiran Schoemacher dalam “Small is Beautiful” menemukan dukungannya dalam pemikiran Illich.
*Kemandirian Energi*
Dalam perspektif ketahanan ataupun kemandirian energi, harus diingat bahwa obsesi pada peningkatan pasokan energi terutama yang terbarukan harus diimbangi dengan pengendalian kebutuhan energi yang sehat. Untuk mencapai target pasokan bauran energi yang lebih berkelanjutan, subsidi BBM harus segera diakhiri agar sumber-sumber energi baru bisa segera memasuki pasar energi.
Potensi besar energi Indonesia yang berada di kawasan cincin api adalah geothermal atau panas bumi. Kita tertinggal jauh dibanding Filipina dalam pengembangan energi panas bumi ini.
Di samping itu, sebagai Negara di daerah katulistiwa, energi matahari yang melimpah perlu lebih dimanfaatkan. Sebagai Negara kepulauan, energi yang bisa ditambang dari laut perlu dimanfaatkan lebih sungguh-sungguh. Di sisi pengendalian kebutuhan energi, ini berarti perubahan gaya hidup yang lebih rendah energi, terutama melalui penetapan batas kecepatan mobilitas, serta pemanfaatan green technology di berbagai bidang seperti green architecture.
Di sektor transportasi, Illich bahkan merekomendasikan agar kecepatan mobilitas kecepatan orang berjalan kaki, atau setara kecepatan maksimum bersepeda. Ini berarti lebih banyak fasilitas transit (pergerakan tanpa mesin) seperti trotoar lebar untuk pejalan kaki, pengguna sepeda, dan kendaraan berkuda terutama untuk perjalanan jarak pendek di perkotaan dan pedesaan yang tidak memerlukan kecepatan tinggi.
Artinya, kemandirian teknologi energi nasional tidak saja diarahkan pada peningkatan kemampuan produksi energi terbarukan di masa depan, tapi juga harus memperhatikan pembudayaan gaya hidup baru dengan teknologi produksi barang dan jasa yang lebih efisien dari segi konsumsi energinya.
Di titik inilah, kita perlu membedakan diri dari China yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia di Abad 21. Jalan Cina, mungkin juga India, adalah jalan yang salah yang sebelumnya telah ditempuh oleh Eropa dan AS. Jika Abad 21 ini disebut sebagai ‘a post-American world’, maka dunia akan segera berada dalam era ‘A post China World’ yang sama salahnya. Model Eropa dan AS telah terbukti gagal, dan oleh karenanya tidak pantas ditiru.
Penutup
Secara umum, dapat dikatakan bahwa upaya kemandirian energi ataupun pangan harus diarahkan pada diversifikasi sumber-sumber energi ataupun pangan. Untuk ketahanan energi, diperlukan kebijakan transportasi yang mendorong angkutan umum dengan moda sungai, rel dan laut yang lebih banyak, serta mengurangi dominansi moda jalan pribadi.
Subsidi BBM harus segera diakhiri agar dananya dapat dialihkan bagi pengembangan sumber-sumber energi baru dan terbarukan.
Kita perlu memilih sebuah jalan baru modernitas, yaitu modernitas energi rendah yang berbeda dengan jalan modernitas yang telah ditempuh Eropa dan AS yang kini sedang diikuti oleh China. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan mereka.
Kita harus memilih modernitas baru yang memberdayakan kapasitas fitrah kita yang dianugerahi Tuhan dengan dua kaki yang tegaknya mencerminkan tahapan evolusi primata paling maju. Kita membutuhkan pengembangan jenis teknologi baru yang menguatkan kedua kaki itu sebagai orang-orang merdeka yang tidak mau dilemahkan oleh mesin-mesin budak energi seperti mobil. Jalan baru itu bukan sekedar kebanggaan kebangsaan yang semu, tapi sekaligus solusi bagi krisis energi di awal Abad 21 ini.(red)
*Oleh : Daniel M Rosyid, PhD.
Pendidik, Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS, Surabaya.