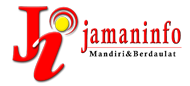#Epenkah (Esai pendek, kah?)
#Onny Wiranda – aktifis 1998 – Alumni LMND – JAMAN Timika
Jamaninfo.com, Sastra – Dalam karya sastra, tak ada si suci atau si jahat abadi, tak ada pahlawan sejati, namun setiap tokoh berpotensi menjadi bajingan atau hero, demikian catat Sunlie Thomas Alexander, esais dari Belinyu itu. Dalam novel Cantik itu Luka karya Eka Kurniawan, Shodancho Supriyadi pemimpin pemberontakan PETA di Blitar itu ternyata seorang penyelundup yang gemar berburu celeng.
Karya sastra memang bukan buku motivasi atau bimbingan rohani. Karya sastra justru mengajak kita memahami kerumitan kehidupan dan menukik ke lubang hitam spiritualisme.
Tidak semua orang bisa ngerti itu. Bahkan yang lulusan Fakultas Sastra sekalipun seperti Fadli Zon. Hidup ini harus jelas gamblang hitam putih. Perkara sejarah, tafsirnya harus tunggal, harus istanasentris.
Nilai tentang pahlawan atau pemberontak adalah warisan cap Orde Baru, kata Andi Achdian, sejarawan dari Universitas Nasional Jakarta. Sejak Prahara 1965, cap sebagai pengkhianat menempel di banyak orang yang punya jasa besar bagi Republik ini.
Bagi Fadli Zon, sejarah itu adalah serangkaian kejadian yang “dia tahu”. Kalau dia “ga tahu” maka kejadian itu ga ada. Pendapat itu bisa berubah setelah didesak tapi berubahnya itu masih dalam batas pikirannya. Misalnya soal pemerkosaan massal 1998 yang disebutnya sebagai “rumor” itu. Awalnya dia ngotot bilang ga ada pemerkosaan massal 1998. Tapi setelah didesak masyarakat dan dicecar DPR, akhirnya dia minta maaf. Contoh berikutnya ya soal Soeharto ini. Awalnya dia bilang ga dengar ada yang mempermasalahkan. Eh setelah dia “dengar,” dia bilang ga percaya kalo Soeharto terlibat dalam Genosida 1965. Saya yakin kalau didesak2 lagi, akhirnya ungkapan pamungkasnya yang pernah dia omongkan di tahun 2021 itu akan muncul, “Pak Harto orang yang menyelamatkan Indonesia dari komunisme 1965-1966.”
Jadi ga masalah kalau ada jutaan orang yang dibantai di tahun 1965, di Tanjung Priok, di Aceh, di Papua, orang Tionghoa ditindas dicabut kewarganegaraanya ga boleh merayakan identitasnya, aktivis mahasiswa hilang sampai sekarang, korupsi, nepotisme keluarga Cendana, tidak diadili karena alasan sakit, seorang jaksa agung mati ditembak karena sedang mengusut kasus anaknya. Semua itu gapapa karena Soeharto sudah menyelamatkan Indonesia dari komunisme. Dalam alasan resminya sekarang ini, katanya karena Soeharto memimpin Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.
Itu sama seperti orang Italia bilang gapapa Mussolini jadi pahlawan nasional Italia karena dia pernah mendirikan kota2 seperti Sabaudia dan Aprilia, dan karenanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang Italia. Tapi orang Italia lebih pintar. Mereka memilih menembak dan menggantung mayat Mussolini terbalik di Milan.
Soal gapapa karena Soeharto punya jasa itu ternyata juga diaminkan oleh orang2 yang pernah berseberangan dengan dia. Salah satunya yang sekarang jadi Wamensos. “Siapapun yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini berhak mendapatkan kehormatan sebagai pahlawan. Siapapun berhak jadi pahlawan,” jawab Agus Jabo di sebuah podcast youtube.
“Siapapun” yang dimaksud oleh Agus Jabo itu tentu adalah Soeharto, bukan Amir Sjarifudin, pendiri Partai Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), tokoh perlawanan di masa pendudukan Jepang, mantan Perdana Menteri Indonesia. Karena rekan sekabinetnya, Fadli Zon, “ga tahu” atau ga menganggap penting penggalan sejarah Indonesia yang itu dalam narasi sejarah yang sedang dibangunnya.
Kita ga akan tahu apa jawaban Agus Jabo kepada anaknya atau murid sekolah yang dikunjunginya setelah melihat foto Soeharto di buku pelajaran sekolah. “Pak, ini orang yang dulu bapak demo kan? Kok dia malah jadi pahlawan sekarang?”
“Yah, namanya juga kehidupan nak. Kita harus berhenti ribut. Kita tutup luka lama,” kata Agus Jabo mengulang jawabannya di podcast youtube, sambil menutup tabletnya setelah menjadi pembicara dalam seminar yang dilakukan secara daring dengan tema, “Buku Sejarah Indonesia yang Baru dan Relevasinya bagi Rekonsiliasi Nasional demi Perwujudan Sepenuhnya Pasal 33 UUD 1945.”
(*)